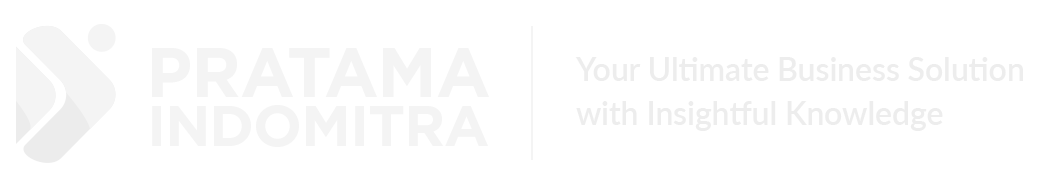Dalam salah satu pemikiran dalam buku The Philosophy of Taxation and Public Finance, Robert W. McGee menyoroti sebuah bentuk pungutan negara yang kerap kita temui tapi jarang kita renungkan secara filosofis, yaitu user fee atau retribusi. Dari tarif air, ongkos masuk taman rekreasi, hingga biaya layanan publik tertentu, retribusi dianggap sebagai cara yang lebih adil dan rasional dibanding pajak.
Retribusi pada dasarnya adalah pungutan yang dikenakan kepada individu yang menggunakan suatu layanan atau fasilitas. Prinsipnya sederhana: siapa yang memakai, dia yang membayar.
Dalam konteks keadilan secara fiskal, pendekatan tersebut lebih unggul karena tidak memaksa orang yang tidak menggunakan layanan untuk ikut menanggung biayanya. Misalnya, bila seseorang membayar tiket masuk ke kebun binatang milik pemerintah, maka ia sedang membayar atas manfaat yang ia nikmati sendiri, bukan disubsidi oleh orang lain yang tidak pernah ke kebun binatang itu.
Dalam dunia nyata, konsep ini sudah diterapkan secara luas: biaya kesehatan di puskesmas, iuran pengangkutan sampah, bahkan biaya langganan air bersih. Semua itu merupakan contoh klasik dari retribusi.
Di satu sisi, retribusi memberi rasa keadilan karena bersifat sukarela. Tidak ada paksaan, jika tidak memakai layanan tersebut maka tidak perlu bayar. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hak milik dan kebebasan individu, hal ini merupakan angin segar.
Namun, persoalan muncul ketika garis batas antara retribusi dan pajak menjadi kabur. Banyak kasus di mana sesuatu disebut retribusi, padahal kenyataannya adalah pajak terselubung.
Contoh klasik bisa kita lihat dari pungutan atas tiket pesawat di Amerika Serikat, yang sebagian besar hasilnya dimasukkan ke dalam Airport and Airway Trust Fund. Awalnya, dana tersebut bertujuan untuk membiayai pemeliharaan bandara dan jalur udara. Namun kenyataannya, jumlah yang dikumpulkan sering kali jauh melampaui kebutuhan aktual.
Alih-alih menurunkan tarif pungutan, pemerintah tetap memungut dengan tarif lama dan menggunakan kelebihannya untuk menambal defisit anggaran. Akibatnya, secara konsep pungutan tersebut bukan lagi retribusi, melainkan pemaksaan dengan bungkus manis.
Hal serupa juga bisa terjadi di Indonesia, terutama ketika prinsip dasar retribusi dilanggar, yakni bahwa yang membayar adalah mereka yang menerima manfaat. Dalam praktik, tidak jarang dana dari retribusi digunakan untuk membiayai sektor yang tidak terkait langsung dengan layanan yang dipakai.
Contohnya dapat ditemukan dalam pengelolaan retribusi parkir di banyak kota besar di Indonesia. Meski retribusi dipungut dari pengguna lahan parkir untuk tujuan penyediaan dan perbaikan fasilitas parkir, realisasi anggaran tersebut justru minim dialokasikan untuk peningkatan kualitas layanan parkir, dan sebagian besar dana masuk ke kas daerah tanpa pelaporan rinci atas pemanfaatannya.
Selain itu, retribusi pelayanan pasar tradisional di beberapa daerah juga dipungut dari pedagang. Namun, kondisi pasar tetap kumuh dan tidak layak, yang mengindikasikan bahwa dana tersebut tidak dikembalikan dalam bentuk peningkatan manfaat bagi para pembayarnya.
Pertanyaan terkait efisiensi dalam pelayanan pemerintah daerah yang dipungut retribusi juga layak diajukan. Salah satu contohnya adalah layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Meskipun RSUD menerima retribusi layanan dari pasien, kualitas layanan yang diberikan tidak jarang dikritik karena waktu tunggu yang lama, pelayanan yang kurang ramah, keterbatasan alat medis, serta birokrasi yang berbelit.
Di sisi lain, banyak rumah sakit swasta mampu memberikan layanan yang lebih cepat, profesional, dan nyaman (meskipun dengan biaya lebih tinggi) dan hal ini mendorong sebagian besar masyarakat kelas menengah ke atas untuk lebih memilih layanan swasta. Bahkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), rumah sakit swasta kini menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan karena mampu memenuhi standar pelayanan minimal yang dibutuhkan masyarakat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: jika sektor swasta terbukti bisa memberikan layanan yang lebih baik dengan sistem manajemen yang lebih efisien, apakah pemerintah daerah masih perlu mempertahankan dominasi dalam penyediaan layanan, atau justru fokus memperkuat fungsi regulasi dan pengawasan?
Lebih dari itu, pergeseran tanggung jawab ke tangan negara secara berlebihan juga membuka peluang untuk penyalahgunaan. Ketika pemerintah ikut campur terlalu dalam dalam penyediaan layanan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh sektor privat, maka pungutan yang semula sukarela berubah menjadi kewajiban yang tak bisa ditolak. Ini melemahkan prinsip kebebasan warga dan memperbesar risiko inefisiensi.
Tentu, tidak semua bentuk keterlibatan pemerintah buruk. Dalam banyak hal, negara tetap dibutuhkan untuk menjamin keadilan sosial dan pelayanan dasar yang merata. Tapi penting untuk diingat bahwa pemerintah bukan satu-satunya penyedia layanan publik. Justru dalam era modern yang ditandai oleh inovasi dan kolaborasi, kita perlu membuka ruang bagi mekanisme pasar untuk ikut hadir menyelesaikan persoalan-persoalan layanan publik.
Sudah saatnya pemerintah daerah berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan yang diberikan. Penarikan retribusi harus disertai dengan perbaikan nyata dalam standar pelayanan, baik dari sisi kecepatan, profesionalisme, maupun transparansi.
Alih-alih mempertahankan peran dominan dalam seluruh lini layanan publik, pemerintah bisa lebih strategis jika memosisikan diri sebagai pengatur dan pengawas, sembari membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian, retribusi tidak lagi menjadi beban, melainkan kontribusi sukarela masyarakat atas layanan yang benar-benar layak mereka terima.