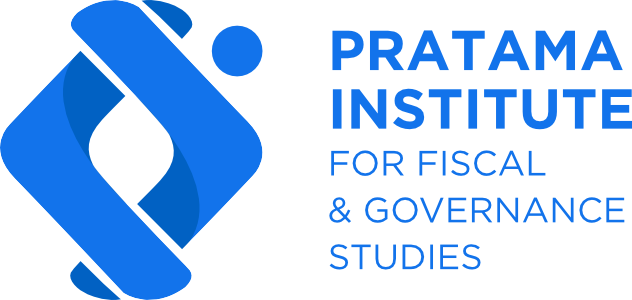Di bulan September ini, DPR disibukkan oleh pengumpulan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari berbagai elemen masyarakat. DIM tersebut terkait dengan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) 2021. Salah satu isu krusialnya ada di Pasal 37E-37I RUU KUP 2021 yang pengaturannya mirip program penghapusan sanksi pajak atau Sunset Policy (SP) Jilid 1 di tahun 2008.
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengungkapkan, hadirnya “SP Jilid 2” dalam RUU KUP 2021 tersebut menunjukkan lemahnya manajemen data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. “Ketentuan tersebut juga menunjukkan ketidakefektifan AEoI (Automatic Exchange of Information) dalam meningkatkan database wajib pajak,” kata Prianto, Jumat (10/9).
Ketentuan SP Jilid 2 yang tertuang di RUU KUP 2021 memberikan fasilitas berupa penghapusan sanksi pajak untuk khusus Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki aset untuk periode 2016 s.d 2019. Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi di program ini. Pertama, perolehan aset WPOP harus di periode 2016 s.d 2019. Kedua, aset pada syarat pertama tersebut masih dimiliki WPOP per tanggal 31 Desember 2019. Ketiga, aset di syarat pertama tersebut belum dilaporkan di dalam SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan) 2019.
Menurut data pemerintah seperti tertuang di Naskah Akademik RUU KUP 2021, ada selisih sebesar Rp 451 triliun yang belum dilaporkan di SPT PPh OP di tahun 2019. Jumlah tersebut diperoleh dengan cara membandingkan harta di SPT PPh OP 2019 dan data AEoI 2019. Jika selisih tersebut dikalikan dengan tarif efektif PPh sebesar 15%, akan diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 67,6 triliun.
Ada empat kelemahan manajemen data AEoI. Pertama, data AEoI tidak menyertakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kedua, alamat pemilik aset keuangan yang tercantum dalam data AEoI tidak lengkap atau berada di luar negeri, sehingga DJP mengalami kendala untuk menindaklanjutinya. Ketiga, DJP tidak menemukan informasi nama dan tanggal lahir pemegang rekening keuangan, sehingga mengalami kendala dalam pelacakan melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan). Keempat, data AEoI tidak mencakup seluruh penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, melainkan hanya mencakup data keuangan.
Kelemahan di atas menunjukkan fakta bahwa data AEoI belum merupakan data matang dan masih harus dilakukan data matching. Dalam hal ini, Ditjen Pajak harus mencocokkan data AEoI dengan data-data lainnya yang Ditjen Pajak terima. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama lagi padahal daluarsa penetapan pajak untuk tahun 2019 akan berakhir setelah 2024. Selain itu, “Kualitas data yang dihimpun oleh kementerian dan lembaga pemerintah juga masih beragam,” ujarnya.
Pada kenyataannya, kata Prianto, Pasal 35A UU KUP mengatur, setiap ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya) wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak. Ketentuan tersebut diperkuat dengan pengesahan UU Nomor 9/2017 yang mengatur Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan demikian, untuk urusan pajak, tidak ada lagi kerahasiaan bank atau pihak lainnya.
Prianto menilai, problem datang dari peraturan pelaksana Pasal 35A UU KUP tersebut yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012. PP tersebut mengatur pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak menjelaskan “standar” kualitas data informasi keuangan yang seharusnya dimiliki oleh ILAP.
Ia mengusulkan, pemerintah sebaiknya merevisi peraturan pelaksana tersebut sehingga tercipta keseragaman data yang dikumpulkan oleh ILAP yang pada ujungnya akan memudahkan pengolahan data tersebut. Menurutnya, revisi PP No. 31/2012 bisa menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan data yang tidak siap guna tersebut.
Prianto menilai, program pengungkapan harta dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak menjadi kurang maksimal jika keempat kelemahan pengolahan data AEoI belum diselesaikan dan kualitas data informasi keuangan belum seragam.