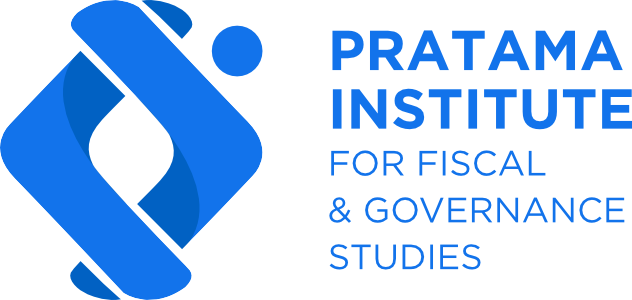Bisnis Indonesia | 29 Desember 2022
Penulis : Prianto Budi Saptono (Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute) dan Lambang Wiji Imantoro (Analis Kebijakan Pajak Pratama-Kreston Tax Research Institute)
Desas-desus mengenai tidak terealisasinya pajak natura dalam waktu dekat mulai menghiasi warta pemberitaan. Maklum saja, hingga Desember 2022 atau 1 tahun pascadisahkannya UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang di dalamnya turut membahas pajak natura, pemerintah hingga saat ini belum juga merancang formulasi aturan teknis penerapan pajak natura.
Setelah gonjang-ganjing pajak natura diulas media, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi rencana pemberlakuan pajak natura dalam waktu dekat. Sejauh ini pemerintah telah menyiapkan 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Satu RPP mengenai PPh, dua RPP mengenai PPN, serta satu RPP lainnya mengenai KUP. Dari 4 RPP tersebut, 1 RPP telah diterbitkan, yaitu PP No. 44/2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah.
Bila menilik target pendapatan negara dalam APBN 2023 yang direncanakan sebesar Rp2.463 triliun dengan proyeksi pendapatan 82,06% atau sekitar Rp1.963 triliun dari sektor perpajakan, rasanya perluasan basis pajak yang satu di antaranya adalah pajak natura menjadi relevan untuk segera direalisasikan. Namun, apakah kebijakan ini akan seutopis yang dibayangkan?
Seiring dengan upaya perbaikan perekonomian, pemerintah mulai gencar memberi stimulus kepada perusahaan/industri (badan) guna menciptakan pertumbuhan perekonomian yang positif. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap hingga 22%.
Di satu sisi, tarif PPh orang pribadi (OP) tidak mengalami penurunan yang berarti. Untuk lapisan penghasilan tertinggi turun menjadi 30%. Namun, pascaperubahan terakhir sesuai UU HPP, terdapat penambahan lapisan penghasilan kena pajak baru, yaitu menjadi 35% untuk mereka yang berpenghasilan di atas Rp5 miliar.
Namun di sisi lain, karena natura dapat dibiayakan, ditambah tarif maksimum PPh badan sekarang hanya 22% yang berasal dari pengenaan pajak di tingkat pemberi kerja, maka penerimaan pajak secara keseluruhan menjadi lebih kecil.
Menilik UU HPP, ada kemungkinan jika pemajakan atas pemberian natura akan dikenakan di tingkat pegawai. Dengan demikian, ada potensi pengenaan pajak yang lebih tinggi, bisa 30% hingga 35%. Pemerintah harus menentukan formulasi yang pas atas pemberlakuan pajak natura terhadap PPh, karena jika natura dikecualikan dari objek PPh jelas berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara yang lebih besar.
Pasca-UU HPP disahkan yang salah satu ketentuannya membahas mengenai pemberlakuan pajak natura, setidaknya ada dua sisi yang akan terjadi jika penerapan pajak natura diberlakukan di UU PPh.
Pertama, dari sisi pemberi kerja yang mencatat biaya natura kepada pegawai untuk perhitungan PPh badan. Sebelum berlakunya UU HPP, pemberian natura dan/atau kenikmatan bukanlah merupakan pengurang penghasilan bruto (non-deductible expense). Namun, pascaberlakunya UU HPP sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh, natura masuk dalam kategori biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (deductible expense).
Kedua, dari sudut pemberi kerja yang berkewajiban memotong PPh 21 atas imbalan pegawai, yang jika ditinjau dari sudut ini, maka imbalan yang dimaksud terdiri atas imbalan tunai maupun nontunai (natura).
Tentu menyusun kebijakan yang tepat terkait dengan pemberlakuan PPh atas natura menjadi PR bagi pemerintah, terutama dalam menentukan klasifikasi objek natura dengan sejelas-jelasnya, mana yang dapat menjadi deductible expense bagi pemberi kerja, dan mana yang nantinya akan menjadi objek PPh 21 bagi karyawan atau pegawai.
Selain pajak natura dapat memberikan efek signifikan pada penerimaan negara, kebijakan ini juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan.
Walau demikian, kebijakan ini juga berpotensi melemahkan semangat pekerja jika tidak dibarengi dengan aturan penerapan yang baik. Seperti pandangan ekonom klasik Alfred Marshall bahwa di balik kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan, terdapat kelemahan yang menurutnya dapat mendorong orang untuk malas bekerja yang ia istilahkan sebagai “menetralkan sikap netral”.
Pemerintah bisa belajar dari New Zealand dalam hal menerapkan kebijakan pajak natura. Tarif pajak natura atau fringe benefit tax (FBT) di New Zealand tergolong paling tinggi di dunia dengan skema tarif final sebesar 63,93%. Di negara tersebut penerapan fringe benefit dibebankan pada perusahaan, dengan metode perhitungan menggunakan gross up of the income tax marginal rates.
Sederhananya, skema penerapan FBT di New Zealand adalah jika seorang pekerja mendapat tunjangan sebesar $100, perusahaan harus membayar tunjangan tersebut sebesar $163,93. Nilai $69,93 merupakan biaya yang ditanggung untuk membayar FBT pekerjanya.
Dampak awal yang dirasakan pada medio 1986–2003 ialah banyaknya praktik penghindaran pajak oleh pengusaha yang terjadi di sana. Selain itu, banyak perusahaan di sana akhirnya enggan memberikan fasilitas tunjangan tambahan seperti asuransi karena enggan berurusan dengan FBT.
Fenomena di New Zealand harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia dalam menerapkan pajak natura pada 2023. Pasalnya, pajak natura akan menjadi simalakama bila tidak dibarengi dengan perencanaan pembuatan peraturan pelaksanaan yang matang.
Artikel ini telah terbit di Harian Kontan dengan judul “Menanti Kejelasan Realisasi Pajak Natura” dengan tautan https://ekonomi.bisnis.com/read/20221229/259/1613100/opini-menanti-kejelasan-realisasi-pajak-natura pada 29 Desember 2022