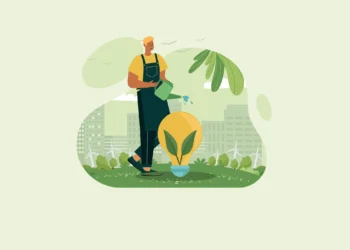Dilansir dari CNBC, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa sistem perpajakan harus dijalankan secara adil dan konsisten, tanpa memberi kesan menghukum atau memeras wajib pajak. Seruan ini bukan sekadar pesan normatif. Ia menyentuh akar persoalan klasik dalam hubungan antara otoritas pajak dan masyarakat: bagaimana perilaku petugas pajak di lapangan dapat membentuk persepsi, bahkan moral pajak, yang akhirnya berdampak langsung pada kepatuhan.
Pajak dan Kesan yang Mengikat
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak wajib pajak di Indonesia masih menganggap pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan, bukan kontribusi sukarela bagi pembangunan. Persepsi ini muncul ketika interaksi dengan petugas pajak lebih sering dikaitkan dengan pemeriksaan, sanksi, atau prosedur yang rumit, alih-alih pelayanan yang membantu.
Studi Putri Indah Wahyuni dkk. (Politeknik Negeri Madiun) menemukan bahwa diskriminasi pajak—ketika wajib pajak kecil merasa lebih ditekan dibanding perusahaan besar—memperkuat kesan bahwa pajak memeras. Sementara itu, penelitian Widjaja & Michael (2024) menyoroti keluhan pelaku UMKM atas tarif dan administrasi pajak yang rumit, yang semakin menurunkan kepatuhan sukarela.
Mengapa Sikap Petugas Sangat Menentukan
Ada sejumlah penjelasan ilmiah yang menunjukkan mengapa perlakuan petugas pajak berpengaruh besar:
Tax Morale – Moral pajak dipengaruhi bukan hanya oleh ancaman sanksi, melainkan juga kepercayaan pada pemerintah dan rasa keadilan. Perlakuan yang intimidatif menurunkan moral pajak.
Slippery Slope Framework – Kepatuhan ditentukan oleh kombinasi power (kekuatan enforcement) dan trust (kepercayaan). Jika petugas hanya menekankan kekuatan tanpa membangun kepercayaan, kepatuhan sukarela merosot.
Perceived Fairness – Keadilan prosedural (proses yang transparan), keadilan distributif (beban pajak yang merata), dan keadilan interaksional (sikap petugas) semuanya membentuk cara wajib pajak menilai otoritas pajak.
Dengan kata lain, perlakuan petugas pajak bukan sekadar etika kerja, melainkan bagian dari strategi kepatuhan itu sendiri.
Dari “Menghukum” ke “Melayani”
Perubahan paradigma diperlukan: dari otoritas pajak sebagai “penagih” yang keras, menjadi mitra yang membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajibannya. Beberapa praktik yang bisa diperkuat antara lain:
Pelayanan ramah dan proaktif – Petugas menjadi fasilitator yang memberi edukasi, bukan sekadar auditor yang mencari kesalahan.
Transparansi prosedur – Wajib pajak tahu apa yang diharapkan, bagaimana proses pemeriksaan, dan hak apa saja yang dimiliki.
Enforcement berbasis risiko – Pemeriksaan ditujukan pada profil risiko tinggi, bukan sekadar mengejar target penerimaan.
Cooperative compliance – Memberi ruang dialog dan insentif bagi wajib pajak patuh.
Studi Daneshwara & Riandoko (2023) menggarisbawahi bahwa ketika kepercayaan pada administrasi pajak tinggi, moral pajak ikut meningkat. Artinya, sikap petugas adalah bagian dari membangun legitimasi institusi.
Baca juga: Mengakhiri Strategi ‘Berburu di Kebun Binatang’ di Sistem Pajak
Implikasi bagi Penerimaan Negara
Dengan target penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun, membangun kepatuhan sukarela wajib pajak adalah keharusan. Mengandalkan pendekatan “menghukum” semata hanya menciptakan resistensi, memperbanyak biaya pengawasan, dan menurunkan legitimasi DJP. Sebaliknya, pelayanan yang adil dan transparan memperkuat rasa memiliki atas kewajiban pajak dan memperluas basis penerimaan jangka panjang.
Pernyataan Purbaya bahwa wajib pajak harus diperlakukan dengan baik adalah pengingat penting bahwa inti dari sistem pajak bukanlah sekadar angka penerimaan, melainkan juga kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia, di mana sebagian masyarakat masih menaruh curiga terhadap otoritas pajak, perilaku petugas di lapangan bisa menjadi jembatan atau justru jurang.
Jika ingin meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan, paradigma “dari menghukum ke melayani” bukan pilihan, melainkan kebutuhan.