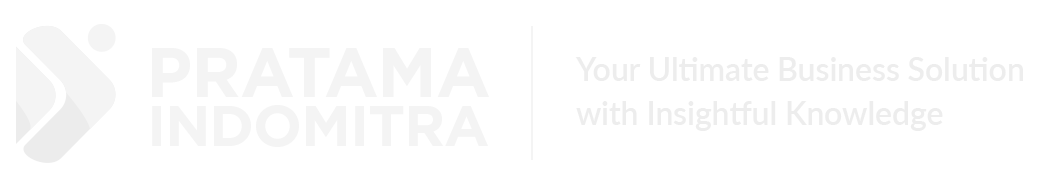Laporan Sustainable Development Report 2023 mencatat bahwa capaian Indonesia atas agenda SDGs berada pada skor 70,4 dari 100. Beberapa area yang masih menunjukkan hambatan signifikan adalah aksi iklim, energi bersih, dan pengelolaan ekosistem daratan. Di sisi lain, OJK melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan melaporkan bahwa pada 2021 terdapat 118 laporan keberlanjutan yang disampaikan ke OJK, atau sekitar 14–15 persen dari total perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan korporasi dalam penyusunan laporan keberlanjutan masih terbatas, meskipun tren partisipasi terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sektor pertambangan menjadi salah satu studi kasus yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara klaim kontribusi dan dampak nyata. Beberapa perusahaan tambang menyatakan dukungan terhadap SDG7 mengenai energi bersih dan SDG8 tentang pekerjaan layak. Namun, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022 mencatat bahwa sekitar 40 persen lahan bekas tambang belum direklamasi. Selain itu, kualitas air di sekitar area tambang batu bara di Kalimantan masih berada di bawah baku mutu lingkungan. Kondisi ini berimplikasi pada tujuan pembangunan lain, terutama kesehatan, pengelolaan air bersih, dan pelestarian ekosistem daratan.
Kesenjangan antara klaim kontribusi dan dampak aktual memperlihatkan bahwa pemetaan sederhana ESG terhadap SDGs tidak cukup untuk menilai kinerja pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif kebijakan ekonomi, hal ini menimbulkan risiko distorsi alokasi modal karena pembiayaan masih mengalir ke sektor yang belum selaras dengan agenda keberlanjutan.
Sistem Keuangan sebagai Mekanisme Penggerak
Keuangan berkelanjutan berperan penting sebagai mekanisme korektif terhadap praktik bisnis yang belum konsisten dengan agenda SDGs. OJK mencatat nilai outstanding obligasi hijau di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp14 triliun pada 2023, meningkat signifikan dibandingkan 2021. Instrumen ini diarahkan untuk membiayai proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Peningkatan nilai obligasi hijau mencerminkan adanya respon pasar terhadap kebutuhan instrumen keuangan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Contoh implementasi dapat ditemukan pada proyek pembangkit listrik tenaga surya di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Proyek tersebut didukung melalui pembiayaan hijau dan berkontribusi meningkatkan bauran energi terbarukan Indonesia yang menurut Kementerian ESDM baru mencapai 14,1 persen pada 2022. Selain mendukung target bauran energi, proyek ini juga menyerap tenaga kerja lokal. Dari sisi kebijakan ekonomi, hal ini memperlihatkan bahwa instrumen keuangan dapat diarahkan untuk menghasilkan dampak ganda berupa pertumbuhan ekonomi sekaligus pencapaian SDGs.
Selain obligasi hijau, tren investasi tematik mulai berkembang. Sejumlah dana ventura domestik menyalurkan modal ke perusahaan rintisan yang bergerak di bidang pertanian berkelanjutan dan inklusi keuangan digital. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa pada 2022 masih terdapat sekitar 51 juta orang dewasa di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan formal. Kehadiran teknologi finansial yang didukung modal berkelanjutan dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat pencapaian SDG1 mengenai pengentasan kemiskinan dan SDG10 terkait pengurangan ketimpangan.
Rekomendasi Kebijakan untuk Integrasi yang Lebih Substansial
Agar ESG dan SDGs dapat berfungsi secara efektif, kebijakan publik di Indonesia perlu diarahkan lebih tegas dan terukur. Pertama, regulasi fiskal dapat digunakan sebagai instrumen insentif dan disinsentif. Implementasi pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perlu dijalankan secara bertahap, sehingga sektor dengan emisi tinggi memiliki dorongan ekonomi untuk melakukan transformasi. Di sisi lain, insentif pajak untuk investasi energi terbarukan atau agroforestry dapat mempercepat realokasi modal menuju sektor yang mendukung SDGs.
Kedua, sistem pelaporan keberlanjutan perlu diperkuat. Regulasi dapat mewajibkan perusahaan menyajikan indikator kuantitatif yang terverifikasi, bukan hanya narasi umum. Praktik di Uni Eropa yang menerapkan prinsip do no significant harm dapat dijadikan acuan, yaitu sebuah aktivitas ekonomi hanya dapat diklaim mendukung SDGs apabila terbukti tidak menimbulkan kerusakan terhadap tujuan lain.
Ketiga, kebijakan publik sebaiknya mendorong perusahaan bergerak dari sekadar mengurangi dampak negatif menuju penciptaan dampak positif bersih. Contoh dapat ditemukan pada perusahaan agribisnis di Sulawesi yang mengembangkan agroforestry bersama petani lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tanah dan menyerap karbon, tetapi juga menaikkan pendapatan petani. Jika praktik semacam ini diperkuat melalui insentif keuangan, maka perusahaan dapat berperan sebagai agen pembangunan sekaligus pemulih ekosistem.
Integrasi ESG dengan SDGs akan menciptakan arah pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih seimbang. Pertumbuhan tidak semata-mata diukur dari peningkatan PDB, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
Informasi Jasa Pratama Institute
Penerapan ESG dilaporkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan yang wajib dibuat setiap tahunnya. Jika Anda ingin memastikan laporan keberlanjutan perusahaan Anda disusun secara profesional dan menarik, kami di Pratama Institute hadir untuk membantu Anda. Dengan pengalaman dan keahlian dalam penyusunan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar terbaik, kami menghadirkan dokumen yang informatif sehingga bisa mencerminkan identitas perusahaan Anda. Hubungi kami untuk solusi laporan keberlanjutan yang ciamik!