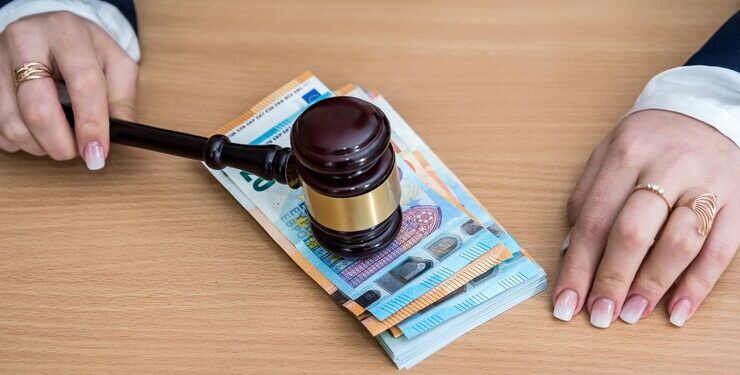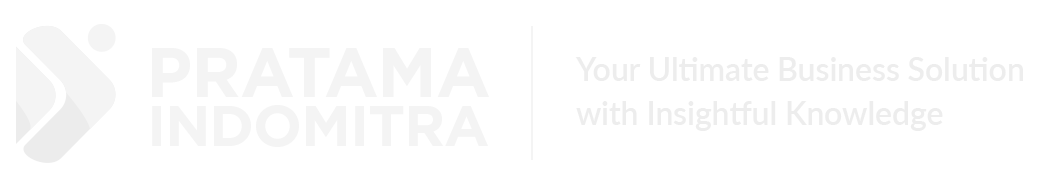Tidak ada orang yang suka dipungut, apalagi jika dipungut dalam bentuk uang. Namun, di balik setiap pungutan yang diwajibkan negara, baik itu pajak, cukai, maupun retribusi, terdapat fondasi pemikiran yang telah berkembang selama berabad-abad.
Jika pungutan negara hanya dilihat sebagai beban atau kewajiban sepihak, maka akan mudah melahirkan penolakan bahkan pembangkangan. Tapi jika kita mau menyelami filosofinya, kita akan menemukan bahwa di balik setiap pungutan negara, terdapat narasi tentang keadilan, tanggung jawab kolektif, dan pengelolaan hidup bersama yang lebih baik.
Setiap rupiah yang ditarik dari masyarakat sejatinya bukan sekadar angka, melainkan bagian dari kontrak sosial yang mengikat antara warga negara dan pemerintah. Karena itu, pemahaman yang mendalam terkait dasar pungutan yang dilakukan negara bisa membangun kesadaran warga untuk terlibat aktif dalam mengawasi dan mengarahkan penggunaan dana publik secara bijak.
Pajak
Pajak adalah bentuk pemungutan yang paling luas dan mendasar dalam sistem keuangan negara. Ia tidak terkait langsung dengan layanan spesifik yang diberikan negara kepada individu, tetapi menjadi cara untuk membiayai kebutuhan kolektif masyarakat secara menyeluruh.
Dalam filosofi klasik, pajak adalah harga yang harus dibayar atas keberadaan negara dan segala manfaat kolektif yang kita nikmati: dari keamanan, infrastruktur, pendidikan, hingga perlindungan hukum.
Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract menyatakan bahwa warga negara menyerahkan sebagian hak miliknya kepada negara demi kepentingan bersama. Karena itu, pajak bukan semata beban individual, melainkan kontribusi bersama untuk memastikan keberlangsungan komunitas politik.
Richard Musgrave (1959) dalam teori public finance mengklasifikasikan fungsi pajak menjadi tiga: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Artinya, pajak tak hanya mengumpulkan uang, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Namun, agar pajak tidak kehilangan legitimasi moralnya, pemungutannya harus adil dan transparan. Pajak yang progresif, di mana orang dengan kemampuan lebih tinggi membayar lebih besar, mencerminkan prinsip vertical equity.
Sebaliknya, bila struktur pajak timpang dan malah memperkuat ketimpangan, ia justru mengkhianati filosofi keadilan sosial yang menjadi ruh dari pemungutan itu sendiri.
Cukai
Berbeda dari pajak, cukai tidak semata digunakan untuk mengumpulkan penerimaan, tetapi juga untuk mengatur perilaku konsumsi masyarakat. Barang-barang seperti rokok, minuman beralkohol, dan produk berbahan plastik atau minuman berpemanis biasanya dikenakan cukai karena dianggap berdampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, atau tatanan sosial.
Filosofi di balik cukai adalah internalisasi eksternalitas, yaitu sebuah prinsip ekonomi yang bertujuan agar biaya sosial dari perilaku konsumsi dimasukkan ke dalam harga barang tersebut.
Arthur Pigou (1920) mengembangkan gagasan ini dalam kerangka Pigovian tax, di mana cukai dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk memperbaiki kegagalan pasar. Ketika individu tidak menanggung sepenuhnya dampak negatif dari tindakannya (seperti polusi dari rokok), maka intervensi negara melalui cukai bisa memaksa mereka menanggung sebagian dari biaya eksternal tersebut.
Di Indonesia, penerimaan dari cukai terus meningkat, bahkan pada 2024 mencapai Rp300,2 triliun, sebagian besar dari cukai hasil tembakau. Filosofi di balik cukai menuntut kita tidak hanya fokus pada angka penerimaan, tetapi pada dampak sosial yang ingin kita capai.
Di antara pertanyaan yang perlu kita jawab: apakah tarif cukai sudah mencerminkan tujuan pengendalian konsumsi? Apakah penggunaannya telah dialokasikan untuk layanan kesehatan atau mitigasi dampak sosial dari barang-barang tersebut?
Retribusi
Retribusi berbeda dari pajak dan cukai karena memiliki hubungan langsung antara pungutan dan manfaat yang diterima oleh pembayar. Ia muncul sebagai imbalan atas pelayanan tertentu yang disediakan pemerintah, seperti retribusi sampah, parkir, terminal, atau izin mendirikan bangunan.
Konsep cukai sejalan dengan benefit principle dalam teori keuangan publik: siapa yang menerima manfaat, dia yang membayar.
Menurut Suparmoko (2000), retribusi merupakan bentuk pembayaran di mana hubungan balas jasa sangat jelas. Artinya, pembayaran retribusi harus proporsional terhadap manfaat atau fasilitas yang diberikan oleh negara. Inilah yang membedakannya secara filosofis dari pajak yang tidak memiliki quid pro quo langsung.
Namun, dalam praktik, retribusi sering kali kehilangan makna filosofisnya. Ketika tarif retribusi ditetapkan tidak rasional, layanan yang diberikan buruk, atau ketika penggunaannya tidak transparan, maka retribusi hanya menjadi alat pemerasan kecil-kecilan oleh pemerintah daerah. Padahal, bila dirancang dengan baik, retribusi bisa menjadi mekanisme yang adil untuk mendanai layanan publik tanpa membebani anggaran negara.
Menyatukan Tiga Instrumen untuk Keadilan Fiskal
Meski memiliki bentuk dan tujuan yang berbeda, pajak, cukai, dan retribusi sama-sama lahir dari kebutuhan dasar negara untuk mengatur dan melayani masyarakat. Mereka tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa ketiga prinsip itu, pungutan negara akan kehilangan legitimasi, bahkan bisa dianggap sebagai tindakan eksploitatif.
Filosofi pemungutan negara juga menuntut adanya keseimbangan. Pajak terlalu tinggi tanpa redistribusi akan menciptakan ketimpangan. Cukai yang hanya fokus pada penerimaan tanpa memperhatikan perubahan perilaku akan menjadi pajak terselubung.
Retribusi yang tidak mencerminkan kualitas layanan hanya akan menambah frustrasi warga. Oleh karena itu, pemahaman filosofis atas ketiganya sangat penting untuk merancang kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.
Dengan berkembangnya diskursus keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dan ekonomi hijau, ketiga instrumen ini juga perlu dimodernisasi. Pajak dapat diarahkan untuk mendukung transisi energi, cukai bisa digunakan untuk mengurangi konsumsi barang-barang merusak lingkungan, dan retribusi bisa disesuaikan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar secara merata.