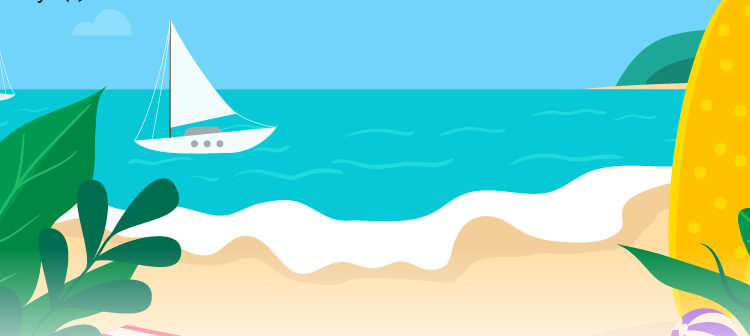Pandemi Corona Virus Desease 2019 (“COVID-19”) dipadukan dengan dinamika global saat ini, reformasi kebijakan perpajakan yang berkelanjutan diperlukan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan menciptakan keseimbangan antara pemerintah, masyarakat, dan ekonomi.
Ketidakpastian ini pada akhirnya menyebabkan pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi kebijakan perpajakan yang mendasar dengan disahkannya Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (“UU HPP”). UU HPP dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (“WP”) secara sukarela.
Penerbitan UU HPP menandakan era baru reformasi perpajakan dengan salah satu poin yang tercantum adalah pengaturan kembali perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan di Indonesia. Pengaturan kembali mengenai penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau pemerintah merupakan objek pajak.
Pengaturan kembali tentang penggantian atau imbalan natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai akan mempengaruhi paradigma sebagian kalangan, tidak hanya fiskus pajak, tetapi juga WP. Pada ketentuan sebelum diberlakukan UU HPP, natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai dianggap sebagai non taxable incomepengeluaran yang dilakukan oleh pemberi kerja atas natura dan/atau kenikmatan tersebut digolongkan sebagai non deductible expense.
Di sisi lain, terdapat beberapa pengecualian seperti natura yang dapat dikenakan pajak bila pemberi kerja merupakan wajib pajak final dan pemberian natura dalam bentuk sesuai yang tertuang dalam PMK Nomor 167/PMK.03/2018. Pengecualian tersebut memicu upaya-upaya tax planning yang tentunya merugikan negara dari segi penerimaan pajak (Dewanto & Wijaya, 2018).
Selain itu, biaya upah dalam bentuk natura yang dilakukan pemberi kerja, secara substansial merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan (Richter, 2006). Dengan demikian, biaya atas natura dan/atau kenikmatan seharusnya dapat digolongkan sebagai deductible sesuai dengan yang tertera pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh. Sejak UU HPP telah diberlakukan pada 29 oktober 2021, dibutuhkan sebuah peraturan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai pengaturan kembali objek natura sebagai objek yang dikenai PPh.
Sesuai dengan amanat UU HPP, ketentuan PPh atas natura dan/atau kenikmatan itu mulai berlaku sejak 1 januari 2022. Akan tetapi, Pemerintah baru saja menerbitkan peraturan turunan dari UU HPP berupa Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 (“PP-55/2022”) pada 20 Desember 2022. Sebagai catatan tambahan, sampai dengan saat ini Pemerintah masih menyiapkan peraturan teknis lanjutan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Pengaturan kembali objek natura sebagai objek PPh dilatarbelakangi oleh kecenderungan perilaku perusahaan sebagai pemberi kerja menggunakan kesempatan (corporate opportunistic behavior) celah pajak (tax loophole) yang merujuk pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (“UU PPh sebelum direvisi menjadi UU HPP”). Adapun perilaku oportunistik ini disebabkan oleh oleh perbedaan tarif PPh Pasal 21 dan tarif PPh Badan sehingga menimbulkan praktik penghindaran pajak secara legal (tax avoidance).
Tabel 1. Persandingan Historis Ketentuan Natura dan/atau Kenikmatan di Indonesia
| Masa Berlaku Pengaturan | Ketentuan Natura dan/atau Kenikmatan di Indonesia |
| UU No. 23 Tahun 1944 (UU PPd) | Imbalan dalam bentuk natura merupakan objek pajak pendapatan (pajak penghasilan) |
| UU No. 7 Tahun 1983 s.d. UU No. 36 Tahun 2008 | Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang dinikmati dalam bentuk natura, dengan ketentuan bahwa yang memberikan penggantian adalah Pemerintah atau wajib pajak. |
| UU No. 36 Tahun 2008 s.t.d.t.d. UU No. 11 Tahun 2020 | Natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah bukan merupakan objek pajak, kecuali natura/kenikmatan yang diberikan oleh:a. bukan wajib pajak b. wajiib pajak yang dikenakan pajak secara final; atau c. wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU PPh |
| UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) | penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau |
Sumber: UU PPd, UU PPh, UU HPP (diolah kembali)
Jika ditelusuri secara historis sejak penerbitan Undang-Undang No. 23 Tahun 1944 tentang Pajak Pendapatan (“UU-PPd”) pada Tahun 1984, imbalan dalam bentuk natura merupakan objek pajak pendapatan (pajak pengasilan). Masadi (1984) menjelaskan bahwa saat itu terjadi kesulitan dalam menilai imbalan natura karena terjadinya perbedaan nilai (harga) imbalan natura. Kesulitan dalam menilai suatu imbalan natura mengakibatkan sulitnya pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari penerima natura. Perlakuan imbalan natura sebagai non-objek PPh berlangsung sejak 1983 dan berakhir pada 2021, ditandai dengan penerbitan UU HPP.
Urgensi Penghindaran Pajak/Tax Avoidance
Sebelum berlakunya UU HPP, natura dan/atau kenikmatan merupakan salah satu instrumen tax avoidance bagi WP. Praktik penghindaran pajak melalui skema pemberian natura dan/atau kenikmatan bagi pegawai terletak pada perbedaan tarif PPh yang dikenakan pada individu orang pribadi dan badan. Pada prinsip pemajakan atas pemberian natura dan/atau kenikmatan adalah beban pajak ditanggung oleh penerima natura dan/atau kenikmatan. Prinsip tersebut kemudian dimanfaatkan oleh WP yang memiliki persyaratan objektif untuk melakukan efisiensi pajak. Dengan adanya celah ini, tentunya potensi penerimaan pajak yang dapat terealisasi akan terkikis. Perlakuan efisiensi pajak melalui pemberian natura dan/atau kenikmatan yang berlaku pada UU PPh sebelum direvisi UU HPP terbagi menjadi dua alternatif.
Alternatif pertama berlaku bagi pegawai yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja dikenakan tarif PPh progresif paling tinggi sebesar 15%. Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berpotensi lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada imbalan dalam bentuk tunai. Keuntungan bagi perusahaan didapatkan melalui penghasilan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek PPh bagi pegawai (taxable) yang dikenakan tarif yang lebih rendah dari pada tarif PPh badan sebesar 22%. Sementara itu, perusahaan dapat mengakui pemberian natura dan/atau kenikmatan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto (deductability). Dengan demikian, skema taxable-deductability mengakibatkan berkurangnya PPh Badan yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan (potential tax loss) karena selisih tarif PPh badan dengan tarif PPh orang pribadi.
Alternatif kedua berlaku bagi pegawai yang memiliki penghasilan dari perusahaan yang menggunakan tarif progresif lebih dari 15% (tarif PPh orang pribadi progresif 15%-30%). Opsi ini memberlakukan skema pemberian natura dan/atau kenikmatan bukan merupakan objek pajak (non-taxability) bagi pegawai dan tidak dapat dibiayakan (non-deductibility) bagi perusahaan. Pada umumnya, perusahaan memberlakukan alternatif kedua bagi pegawai yang memiliki jabatan tinggi (top level management) dengan pemberian tunjangan rumah, kendaraan, dan tunjangan lainnya. Skema pemberian natura dan/atau kenikmatan melalui opsi kedua ini cenderung membebankan tunjangan yang diterima oleh pegawai dengan jabatan tinggi kepada perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka.
Perencanaan pajak melalui alternatif kedua memiliki dampak pada berkurangnya nilai PPh 21 yang harus dibayar oleh para karyawan top level dan mengalihkan beban pajak pada perusahaan. Berkurangnya nilai pajak yang harus dibayar oleh para karyawan top level tentunya akan berimplikasi pada keberhasilan fungsi redistribusi pajak.
Sejak berlakunya UU HPP dengan mencantumkan pengaturan kembali PPh atas natura dan/atau kenikmatan me regulasi sebelumnya dengan harapan menutup celah tax avoidance. UU HPP beserta aturan turunannya menetapkan bahwa pemberi kerja hanya memiliki satu opsi untuk memberlakukan natura dan/atau kenikmatan agar diklasifikasikan sebagai deductible bagi pemberi kerja dan taxable bagi penerima. Perubahan regulasi ini mendorong pemberi kerja untuk mengurangi nilai gaji dan meningkatkan jumlah natura dan/atau kenikmatan yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai.
Pemberian natura dan/atau kenikmatan yang seharusnya dikategorikan sebagai nondeductible expense diubah menjadi jenis akun lain yang dikategorikan sebagai deductible expense, misalnya gaji. Hal ini juga didukung dengan sulitnya melakukan tracing sehingga akan sangat rumit untuk bisa membuktikan apakah biaya yang telah dikeluarkan ditujukan untuk pemberian natura dan/atau kenikmatan. Beragam praktik tax avoidance tersebut akhirnya memunculkan urgensi untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat memitigasi risiko-risiko tersebut ke depannya.
Maka dari itu, UU HPP hadir sebagai angin segar khususnya terkait permasalahan tax avoidance pada aspek perpajakan natura dan/atau kenikmatan. Dengan menetapkan natura dan/atau kenikmatan sebagai taxable-deductible, celah tax avoidance diharapkan dapat dicegah dan upaya pemerataan serta keadilan dapat tercapai. Hal ini akan berdampak pada rendahnya proporsi biaya yang dapat dibebankan secara fiskal bagi perusahaan sehingga pajak atas penghasilan badan yang dikenakan akan bertambah dan di sisi lain nilai pajak penghasilan orang pribadi penerima natura dan/atau kenikmatan akan jauh lebih kecil.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, regulasi sebelum UU HPP berkaitan dengan aspek perpajakan natura dan/atau kenikmatan telah menimbulkan distorsi pada perekonomian dengan meletakkan beban pajak pada badan/perusahaan. Maka dari itu, regulasi dalam UU HPP yang menetapkan natura dan/atau kenikmatan
sebagai taxable-deductible menjadi titik awal optimalisasi perpajakan khususnya dari segi PPh orang pribadi.
Pemajakan yang dilakukan terhadap natura dan/atau kenikmatan akan mengeruk potensi penerimaan perpajakan yang cukup besar dari karyawan top level dan tidak akan memberatkan karyawan low level. Selain itu, regulasi dalam UU HPP juga berusaha untuk lebih berfokus pada aspek taxable income daripada deductibility pada natura dan/atau kenikmatan sehingga beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan lebih rendah dan diharapkan dapat mengurangi distorsi pada perekonomian.
Pada sisi pengawasan, pengaturan kembali PPh atas natura dan/atau kenikmatan dimasukdalam objek pemotongan PPh Pasal 21 diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan kepatuhan WP dan perusahaan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa mengawasi pelaporan SPT PPh 21 oleh pemberi kerja akan jauh lebih efektif dari pekerjaan mengawasi pelaporan SPT PPh orang pribadi pegawai dari pemberi kerja tersebut. Secara sederhana, bahwa mengawasi laporan pajak satu pemberi kerja yang mempekerjakan 1.000 pegawai akan lebih efektif dan efisien dari mengawasi 1.000 laporan pajak pegawainya.
Rekomendasi
Secara konsep, Thuronyi (1996) menjelaskan bahwa sebaiknya perumus kebijakan membuat sebuah kebijakan tentang klasifikasi objek natura melalui pendekatan daftar objek natura yang dikenai PPh (positive list). Selanjutnyabertahap perumus kebijakan dapat menyusun daftar objek natura yang termasuk non-objek
PPh (negative list). Pendekatan kombinasi positive list dan negative list dapat saling melengkapi dan mengedepankan asas kepastian bagi seluruh subjek yang menerima natura. Jika penentuan objek natura hanya berdasarkan pada negative list, dapat berpotensi adanya multitafsir interpretasi objek natura yang dapat dijadikan objek PPh sehingga menimbulkan sengketa antara otoritas dan WP.
Perumus kebijakan dapat mengantisipasi potensi sengketa yang dapat timbul dari multitafsir terkait objek natura dengan menerapakan kebijakan de minimis fringe benefit, seperti yang telah dilaksanakan oleh Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat. Kebijakan de minimis fringe benefit memungkinkan perumus kebijakan untuk menyusun batasan-batasan tertentu dari jumlah nilai imbalan natura dan kenikmatan agar dikecualikan dari objek PPh. Pembatasan ini diberlakukan bertujuan untuk mengurangi kesulitan dalam memperhitungkan nilai imbalan natura yang nantinya akan diperhitungkan sebagai objek PPh oleh penerima imbalan.
Penyusunan batasan tertentu dengan kebijakan de minimis fringe benefit telah sesuai dengan ketentuan tentang adanya objek natura yang dikecualikan dari objek PPh dengan mempertimbangkan jenis dan/atau batasan tertentu. Pengaturan ini tercantum pada Pasal 24 huruf e Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022,
kemudian diperjelas kembali oleh Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai perumus kebijakan perlu memerhatikan penerapan de minimis fringe benefit pada tingkat kewajaran frekuensi suatu pemberian imbalan natura. Jika suatu imbalan natura berada dih batasan deminimis, DJP sebaiknya mempertimbangkan frekuensi dan nilai dari imbalan natura tersebut.
Salah satu elemen penting dalam penerapan de minimis adalah tingkat kewajaran frekuensi imbalan natura, jika pemberian imbalan dalam jumlah kecil tapi dilakukan dengan kuantitas banyak dapat dicurigai sebagai kompensasi terselubung.
Sesuai pernyataan Thuronyi (1996) sebaiknya perumus kebijakan menyusun kebijakan tentang klasikasi objek natura melalui pendekatan kombinasi positive list dan negative list agar lebih memberikan kepastian hukum dan menghindari multitafsir di. Jika perumus kebijakan merasa pendekatan kombinasi tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia, sekurang-kurangnya perumus kebijakan dapat memberlakukan de minimis fringe benefit sebagai solusi alternatif.