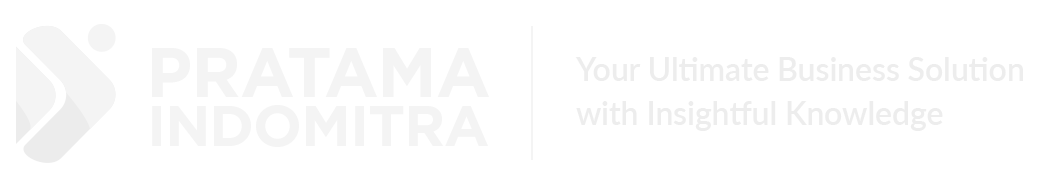Dalam menghadapi gejolak ekonomi global yang tidak menentu serta tantangan domestik seperti ketimpangan, pengangguran, dan inflasi, pemerintah Indonesia secara aktif menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama untuk menstimulasi perekonomian. Salah satu wujud konkrit dari strategi tersebut adalah pemberian insentif fiskal, baik dalam bentuk pengurangan beban pajak, subsidi, bantuan langsung tunai, hingga stimulus sektoral.
Namun, seiring bertambahnya beban fiskal dan keterbatasan ruang anggaran, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana insentif-insentif tersebut efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis? Secara teoritik, insentif fiskal merupakan bagian dari kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi dengan memperbesar disposable income masyarakat atau menurunkan biaya produksi sektor usaha.
Dalam konteks Indonesia, insentif fiskal telah digunakan secara masif terutama sejak pandemi COVID-19 merebak pada 2020. Pada saat pendemi Covid-19 di 2020 lalu, Pemerintah menggelontorkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total Rp579,78 triliun, yang meningkat menjadi Rp744,77 triliun pada 2021. Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk perlindungan sosial dan dukungan sektor usaha, termasuk bantuan langsung tunai, subsidi listrik, pembebasan PPh final UMKM, dan diskon PPN sektor properti dan otomotif.
Efektivitas Insentif Fiskal
Jika dilihat dari sisi konsumsi rumah tangga, insentif tersebut memang sempat memberikan bantalan penting. Pada kuartal II tahun 2020, ketika pandemi mencapai puncaknya, konsumsi rumah tangga Indonesia terkontraksi -5,52 persen. Namun, setelah berbagai insentif dikucurkan, laju kontraksi mulai menurun dan akhirnya kembali tumbuh positif pada kuartal II tahun 2021 sebesar 5,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi fiskal berhasil menjaga daya beli dalam jangka pendek, terutama bagi kelompok rentan.
Namun efektivitasnya menjadi lebih kompleks ketika ditinjau dari aspek keberlanjutan dan ketepatan sasaran. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 menyebutkan bahwa sebagian bantuan sosial dan insentif fiskal selama pandemi tidak tepat sasaran. Sebanyak 10 juta data penerima bansos ditemukan ganda atau tidak valid. Selain itu, penyaluran insentif sektor informal masih jauh dari optimal karena banyak pelaku usaha mikro tidak terdaftar dalam sistem perpajakan atau tidak memiliki akses perbankan yang memadai. Dengan kata lain, meski insentif tersedia, daya serapnya di level akar rumput masih terbatas.
Sementara dari sisi dukungan terhadap sektor strategis, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai insentif untuk mendorong pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Sektor manufaktur, yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, mendapatkan fasilitas seperti tax holiday dan super deduction tax untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) serta pelatihan vokasi.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019, misalnya, memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen untuk perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja. Namun, menurut data Kementerian Keuangan, realisasi pemanfaatan insentif ini masih minim. Hingga tahun 2022, hanya sekitar 30 perusahaan yang mengakses fasilitas super deduction tax untuk vokasi, dan sebagian besar berasal dari korporasi besar, bukan UMKM.
Demikian pula dalam sektor pariwisata, insentif fiskal seperti diskon tiket pesawat dan hibah ke daerah pariwisata sempat diberikan pada tahun 2020-2021. Namun, dampaknya tidak cukup signifikan karena pembatasan mobilitas dan lemahnya permintaan masyarakat. Menurut data BPS, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDB baru pulih ke level pra-pandemi pada akhir 2023, menunjukkan pemulihan yang lambat meski disokong insentif.
Insentif Fiskal Rawan Ciptakan Moral Hazard?
Salah satu masalah utama dari pemberian insentif fiskal di Indonesia adalah kecenderungan desain kebijakan yang terlalu bersifat jangka pendek, berbasis anggaran tahunan, dan kurang terintegrasi dengan kebijakan struktural lainnya. Alih-alih menjadi alat yang mendorong transformasi ekonomi, insentif fiskal sering kali digunakan sebagai “pemadam kebakaran” untuk merespons krisis. Tidak heran bila efeknya cepat menguap begitu stimulus dihentikan.
Dalam beberapa kasus, insentif juga rawan menciptakan distorsi pasar dan moral hazard. Misalnya, pemberian tax holiday kepada investor asing yang tidak dibarengi dengan kewajiban transfer teknologi atau penciptaan lapangan kerja berkualitas hanya akan memperkuat ketergantungan pada modal luar tanpa meningkatkan kapasitas domestik. Bahkan, studi dari OECD (2021) menunjukkan bahwa insentif pajak yang tidak transparan dapat menjadi ladang penyalahgunaan dan merugikan negara hingga 1-2 persen dari PDB setiap tahunnya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.
Selain efektivitasnya yang masih dipertanyakan, sistem monitoring dan evaluasi (M&E) dari kebijakan insentif fiskal juga relatif lemah. Pemerintah jarang melakukan evaluasi berbasis data terhadap hasil dari pemberian insentif tertentu. Akibatnya, banyak program yang terus dilanjutkan meski tidak memberikan hasil optimal. Misalnya, insentif PPN 0 persen untuk rumah dengan harga tertentu pernah dikritik karena justru menguntungkan segmen masyarakat menengah ke atas, sementara kelompok bawah tetap kesulitan mengakses hunian layak.
Ke depan, efektivitas insentif fiskal dapat ditingkatkan melalui beberapa pendekatan. Pertama, desain insentif perlu diarahkan untuk mendukung agenda transformasi struktural seperti industrialisasi hijau, digitalisasi UMKM, dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Insentif tidak hanya untuk meredam gejolak, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi sektor strategis. Kedua, perlu ada penguatan data terpadu berbasis NIK dan integrasi antara kebijakan fiskal, sosial, dan ketenagakerjaan agar intervensi lebih tepat sasaran. Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi harus diperkuat, dengan indikator keberhasilan yang jelas dan transparan. Laporan berkala tentang dampak insentif fiskal harus menjadi bagian dari akuntabilitas publik.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting dalam menentukan skema insentif yang kontekstual. Misalnya, daerah dengan potensi industri kreatif dapat diberikan insentif berbasis kawasan untuk mengembangkan ekosistem usaha mikro dan start-up. Pendekatan semacam ini memungkinkan insentif fiskal tidak hanya sebagai alat stabilisasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan jangka panjang.
Pada akhirnya, insentif fiskal hanya akan efektif jika dijalankan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan disertai dengan reformasi struktural lainnya. Menjaga daya beli masyarakat bukan hanya tentang memberi bantuan, tetapi tentang membangun sistem ekonomi yang adil dan inklusif.
Demikian pula, mendorong sektor strategis tidak cukup dengan pemotongan pajak, melainkan memerlukan dukungan dalam bentuk regulasi yang kondusif, infrastruktur yang memadai, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, kebijakan fiskal Indonesia akan benar-benar mampu menjadi jangkar pemulihan dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.