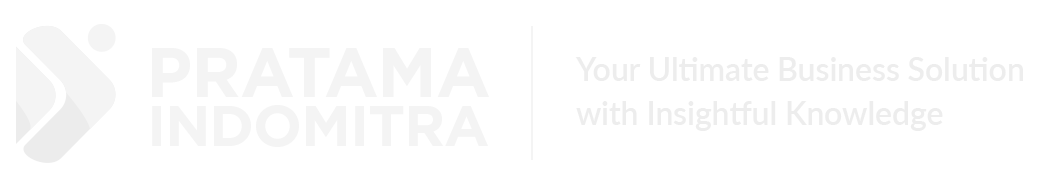Dalam diskursus lingkungan global saat ini, kota metropolitan seperti Jakarta kini berada di titik balik antara melanjutkan model pembangunan eksploitatif atau mengakselerasi reformasi struktural menuju kota rendah emisi. Bukan tidak mungkin Jakarta menerapkan kebijakan yang sangat patut diapresiasi ini, meski pasti akan menghadapi sejumlah tantangan besar. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya telah membaca arah zaman: krisis iklim bukan lagi tantangan ekologis semata, melainkan soal tata kelola ekonomi yang menentukan keberlanjutan kota dan warganya. Maka, penetapan target yang cukup ambisius menuju net zero emission pada 2050, sepuluh tahun lebih awal dari target nasional, perlu dibedah lebih dalam — apakah ini sekadar normatif, atau benar-benar ditopang oleh desain kebijakan publik yang sistemik dan efektif?
Kawasan Rendah Emisi: Intervensi Struktural atau Sekadar Simbolik?
Penerapan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) merupakan langkah taktis yang menandai niat politik Pemprov DKI untuk melakukan intervensi pada sektor transportasi dan mobilitas perkotaan — penyumbang emisi terbesar di kota ini. Menurut Jakarta Environmental Agency, sektor transportasi berkontribusi hampir 60% terhadap emisi karbon Jakarta (DLH DKI, 2023). Sejak tahun 2020, Pemprov telah menginisiasi zona rendah emisi di Kota Tua dan Tebet Eco Park, namun skala dan dampaknya masih bersifat terbatas.
Langkah memperluas KRE-T, seperti yang tengah dikaji bersama C40 Cities dan Breathe Cities, patut diapresiasi. Namun kita harus mencermati: apakah perluasan ini akan benar-benar berdampak secara struktural atau sekadar menjadi proyek showcase lingkungan? Bila dilihat dari pendekatan ESG, terutama pilar Environmental, kebijakan seperti KRE-T harus mampu memicu spillover positif seperti konversi kendaraan pribadi ke transportasi publik, perbaikan kualitas udara, serta peningkatan partisipasi publik terhadap program lingkungan.
Efek Multiplier yang Masih Lemah
Dalam desain kebijakan publik, kebijakan rendah emisi harus terkoneksi secara integratif dengan sistem transportasi perkotaan. Pemerintah pusat dan DKI telah mengembangkan Transit-Oriented Development (ToD) di beberapa titik, serta memperluas sistem ganjil-genap. Namun, data Bappenas (2024) menunjukkan bahwa rasio perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke transportasi umum di Jakarta baru mencapai 35%, masih jauh dari angka ideal 60–70% untuk menekan emisi signifikan.
Tak hanya itu, kebijakan seperti larangan pembakaran sampah terbuka, ProKlim, serta pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik belum menyentuh akar masalah: kemiskinan energi dan aksesibilitas bagi masyarakat kelas bawah. Di sinilah prinsip Social dalam ESG perlu ditekankan — bahwa transisi hijau harus inklusif. Intervensi seperti pembangunan jalur sepeda atau insentif kendaraan listrik harus diimbangi dengan skema subsidi transportasi umum untuk kalangan rentan.
Polusi Udara Masih Menghantui
Meski kebijakan mulai bergulir, hasilnya belum nampak terhadap kondisi lingkungan faktual. Berdasarkan laporan IQAir (2024), Jakarta termasuk dalam 10 besar kota paling tercemar di dunia, dengan indeks AQI yang sering menyentuh level very unhealthy. Hal ini memperkuat dugaan bahwa desain kebijakan yang ada masih terputus dan minim evaluasi dampak lingkungan secara berkala.
Bahkan, analisis Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menemukan bahwa konsentrasi PM2.5 di Jakarta rata-rata mencapai 38 µg/m³, jauh melebihi ambang batas WHO sebesar 5 µg/m³. Ini bukan sekadar angka teknis, tapi indikator bahwa kebijakan yang ada nyatanya belum mampu mengintervensi sumber utama emisi secara efektif.
Pentingnya Revisi Desain Kebijakan dan Evaluasi
Mengacu pada teori policy feedback dan ecological modernization, kebijakan lingkungan seperti KRE-T hanya akan sukses jika diintegrasikan dalam sistem tata ruang dan ekonomi kota. Beberapa hal yang perlu dipertimbngkan dalam rangka perbaikan desain kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah DKI Jakarta, antara lain:
- Perluasan berbasis kebutuhan dan polusi aktual:
Zona rendah emisi perlu ditetapkan berdasarkan data hotspot emisi, bukan sekadar kawasan pariwisata atau ekonomi tinggi. - Infrastruktur pendukung transportasi publik dan kendaraan rendah emisi:
Harus ada akselerasi pembangunan Electric Vehicle Charging Station (EVCS) dan jalur sepeda yang aman dan terhubung ke titik transportasi umum. - Skema insentif fiskal dan pembiayaan hijau:
DKI Jakarta dapat mengembangkan obligasi hijau (green bonds) atau dana lingkungan untuk mendukung pembiayaan transisi energi perkotaan. - Evaluasi kuantitatif dan partisipatif:
Setiap program perlu dievaluasi berbasis indikator dampak (misal: penurunan PM2.5, peningkatan pengguna Transjakarta) dan melibatkan masyarakat.
Menata Kota, Merawat Masa Depan
Dalam konteks ESG dan pembangunan berkelanjutan, keberanian Pemprov DKI Jakarta menargetkan net zero emission pada 2050 patut diapresiasi, tapi juga perlu diuji dan dipertimbangkan dengan akuntabilitas kebijakan. Narasi yang sangat serius ini harus dijembatani dengan aksi konkret, data terbuka, dan kolaborasi lintas sektor, serta dukungan pihak terkait. Tanpa itu semua, KRE-T dan sejenisnya berisiko menjadi hanya ide dekorasi kota, bukan solusi untuk krisis iklim.
Jika Jakarta bisa menjadi laboratorium kebijakan transisi hijau yang serius, maka kota-kota lain di Indonesia akan memiliki model yang bisa direplikasi — dan negara ini akan punya pijakan kuat dalam diplomasi iklim global.
Informasi Jasa Pratama Institute
Penerapan ESG dilaporkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan yang wajib dibuat setiap tahunnya. Jika Anda ingin memastikan laporan keberlanjutan perusahaan Anda disusun secara profesional dan menarik, kami di Pratama Institute hadir untuk membantu Anda. Dengan pengalaman dan keahlian dalam penyusunan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar terbaik, kami menghadirkan dokumen yang informatif sehingga bisa mencerminkan identitas perusahaan Anda. Hubungi kami untuk solusi laporan keberlanjutan yang ciamik!