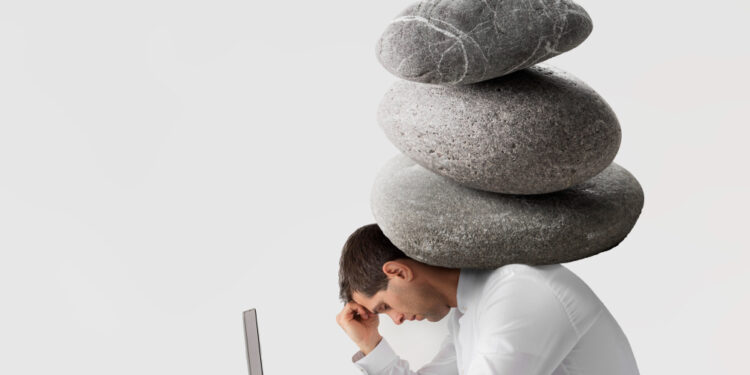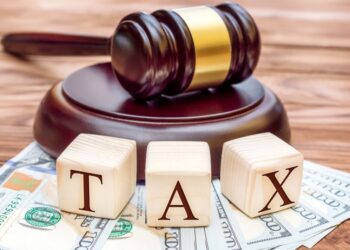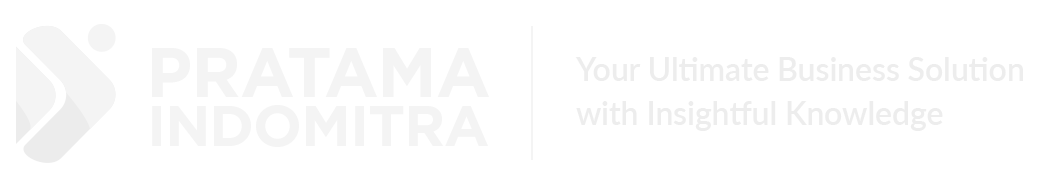Laporan E-Conomy SEA 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan fakta menarik: ekonomi digital Indonesia pada 2024 mencapai nilai US$90 miliar, naik 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, penetrasi internet yang masif, serta menjamurnya platform e-commerce, Indonesia menjadi ladang subur bagi pertumbuhan ekonomi digital.
Namun, pertanyaan mendasar pun muncul: bagaimana negara memastikan bahwa geliat ekonomi digital tersebut juga bermuara pada penerimaan pajak yang adil dan berkelanjutan? Pemerintah sejatinya sudah melakukan berbagai upaya. Sejak 2020, Kementerian Keuangan memperkenalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), agar transaksi digital tidak luput dari kewajiban perpajakan. Pada 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan core tax administration system (CTAS) untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan pajak.
Langkah terbaru, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025), yang mewajibkan marketplace memungut Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen dari para penjual. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperluas basis pajak sekaligus menciptakan level playing field antara pedagang offline dan online.
Beban Tambahan bagi UMKM
Meski niatnya baik, kebijakan PMK 37/2025 menimbulkan persoalan serius. Skema pemungutan PPh 0,5 persen oleh marketplace berpotensi menekan pelaku UMKM di ekosistem e-commerce. Angka 0,5 persen memang terlihat kecil, tetapi bagi pelaku usaha dengan margin keuntungan tipis, beban ini sangat signifikan. Skema tersebut bersifat presumptive tax: dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masing-masing usaha.
Logika level playing field yang dijadikan pembenaran juga patut dipertanyakan. UMKM online memang tidak membayar sewa kios fisik, tetapi mereka menghadapi biaya lain yang tidak kalah berat, seperti ongkos logistik, biaya iklan digital untuk mendapatkan traffic, hingga biaya layanan yang dipungut marketplace. Ketika pemerintah menyamakan beban antara pedagang offline dan online, sesungguhnya ada realitas biaya yang diabaikan. Akibatnya, yang muncul bukan keadilan, melainkan ketimpangan baru.
Bahkan, kebijakan ini berisiko menimbulkan efek balik. Jika beban pajak dianggap terlalu berat, sebagian pelaku UMKM bisa memilih keluar dari ekosistem formal e-commerce dan kembali ke kanal penjualan informal yang sulit terpantau. Alih-alih memperluas basis pajak, pemerintah justru berisiko kehilangan potensi penerimaan. Lebih jauh, biaya administrasi dan pengawasan dari jutaan pelaku UMKM bisa lebih besar dibanding penerimaan yang dihasilkan.
Arah Pajak Digital Berpotensi Salah Sasaran
Ironisnya, perhatian besar justru diarahkan pada pelaku kecil, sementara potensi besar dari perusahaan raksasa digital global belum tergarap optimal. Data DJP mencatat, sepanjang 2024 penerimaan PPN dari kegiatan usaha PMSE hanya Rp5,39 triliun. Bandingkan dengan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia yang mencapai US$90 miliar, atau lebih dari Rp1.400 triliun. Angka tersebut jelas tidak sebanding.
Padahal, raksasa digital seperti Google, Meta, Spotify, Netflix, hingga platform e-commerce global memperoleh keuntungan masif dari pasar Indonesia. Namun, kontribusi pajak mereka masih sangat terbatas, sebagian besar hanya melalui skema PPN PMSE. Penerimaan PPh dari perusahaan-perusahaan ini relatif kecil karena banyak dari mereka tidak memiliki permanent establishment di Indonesia. Dengan kata lain, perusahaan global bebas menikmati pasar domestik, tetapi kontribusi mereka pada kas negara jauh dari proporsional.
Masa Depan Penerimaan di Era Digital
Dalam situasi ini, kebijakan perpajakan digital seharusnya berfokus pada dua hal: ekstensifikasi pajak kepada perusahaan digital global, serta intensifikasi pengawasan pada potensi pajak yang memang signifikan. Pemerintah bisa belajar dari negara-negara lain yang berani mengenakan digital services tax untuk memastikan kontribusi perusahaan raksasa digital sesuai dengan keuntungan yang mereka raih dari konsumen lokal.
Alih-alih membebani UMKM dengan pungutan tambahan, lebih baik pemerintah memaksimalkan potensi pajak dari perusahaan besar yang relatif lebih mudah dipantau. Dari perspektif efisiensi, memungut pajak dari segelintir perusahaan global tentu lebih murah dibanding membidik jutaan UMKM yang rata-rata beromzet kecil. Dari perspektif keadilan, langkah ini juga lebih tepat: kontribusi negara berasal dari pihak yang paling banyak menikmati keuntungan dari ekonomi digital.
Masa depan penerimaan negara di era digital akan ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam menata kebijakan fiskalnya. Jika orientasi kebijakan terus menekan kelompok kecil demi tambahan penerimaan jangka pendek, Indonesia berisiko mengorbankan UMKM yang justru menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Namun, jika pemerintah berani menutup celah perpajakan dari perusahaan raksasa digital global, hasilnya bukan hanya penerimaan yang lebih besar, melainkan juga keadilan fiskal yang lebih nyata.
Kita tentu sepakat bahwa penerimaan pajak merupakan urat nadi pembangunan. Tetapi keadilan dalam pemungutan pajak harus menjadi fondasi utama. Jangan sampai era digital justru menghadirkan paradoks: UMKM lokal yang berjuang dengan margin tipis dibebani pajak, sementara perusahaan global dengan laba raksasa bisa melenggang bebas dengan kontribusi minim.
Di titik inilah masa depan perpajakan digital Indonesia dipertaruhkan. Pemerintah harus menentukan pilihan, terus membebani yang kecil, atau berani menagih yang besar?