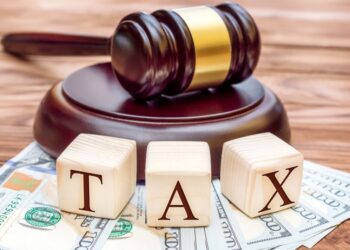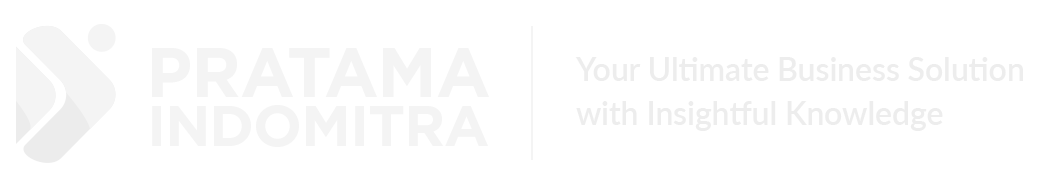Tanggal 8 September 2025 lalu, Indonesia resmi memiliki Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Salah satu sikap keras yang langsung ia tunjukkan adalah menolak program pengampunan pajak (tax amnesty). Penolakan ini muncul setelah isu pengampunan pajak kembali ramai, seiring dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 2025 serta RUU jangka menengah 2025–2029.
Bagi sebagian orang, sikap Purbaya ini mungkin mengejutkan. Bagaimana tidak, program pengampunan pajak pernah menjadi “primadona” kebijakan fiskal Indonesia. Namun, argumennya sederhana: pengampunan pajak yang berulang hanya akan memicu perilaku tidak patuh. Wajib Pajak bukannya rajin bayar, malah bisa jadi terbiasa menunda dengan harapan nanti ada “diskon” atau amnesti lagi. Lantas, benarkah program pengampunan pajak sudah saatnya dihentikan?
Indonesia bukan pemain baru dalam kebijakan pengampunan pajak. Pertama kali, pengampunan pajak dilakukan tahun 1964 dalam era kepemimpinan Soekarno. Yang kedua, di tahun 1984 dalam kepemimpinan Soeharto. Tidak berhenti sampai di situ, di tahun 2008 diadakan kebijakan sunset policy dan di tahun 2016 diadakan program amnesti pajak. Yang terakhir, adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di tahun 2022 melalui UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pola yang terlihat, amnesti pajak biasanya dilakukan setiap lebih dari lima tahun sekali. Alasan utamanya jelas, yaitu memperluas basis data perpajakan (ekstensifikasi). Setelah basis diperluas, barulah dilakukan optimalisasi atau intensifikasi untuk memaksimalkan penerimaan negara dari basis yang sudah ada.
Kita ambil contoh dua program terakhir, program amnesti pajak 2016 bisa dibilang sukses besar. Harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.720 triliun. Angka itu fantastis karena memberi tambahan basis pajak baru. Prinsip sederhananya, penghasilan seseorang bisa dilihat dari konsumsi dan hartanya. Jika harta yang sebelumnya disembunyikan dan saat tax amnesty berlaku akhirnya tercatat maka peluang pajak yang bisa dipungut juga bertambah. Namun, cerita berbeda pada program pengampunan pajak di tahun 2022 lewat PPS. Total harta yang dideklarasikan hanya sebesar Rp594,82 triliun, turun drastis Rp4.125 triliun dibanding program 2016. Penurunan ini mengindikasikan masyarakat tidak lagi antusias pada program PPS. Program ini dianggap tidak menarik mungkin karena terlalu dekat jaraknya dengan amnesti sebelumnya. Fenomena ini memberi sinyal bahwa semakin sering amnesti digelar, semakin menurun daya tarik dan efektivitasnya.
Bahaya Amnesti Berulang
Menteri Keuangan yang baru dilantik pada September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa amnesti berulang justru bisa merusak kepatuhan. Alih-alih patuh setiap tahun, masyarakat bisa berpikir, “Ah, toh nanti juga ada amnesti lagi.” Tanggapan Menkeu tersebut menegaskan pelaksanaan tax amnesty berulang kali berpotensi merusak kredibilitas sistem perpajakan Indonesia. Kebijakan semacam itu bisa memberi sinyal keliru kepada wajib pajak seolah-olah pelanggaran aturan dapat ditoleransi karena nantinya akan selalu ada program amnesti berikutnya.
Rencana program pengampunan pajak jilid 3 juga menimbulkan risiko yang semakin besar di tengah kondisi sosial-politik yang tidak stabil. Sejumlah pihak menyuarakan dukunganya dengan pernyataan Menkeu Purbaya agar menolak wacana amnesty. Selain itu, sebagai bentuk protes terhadap pemerintah muncul tren “stop bayar pajak”. Melihat kondisi demikian, Pemerintah dituntut untuk memberikan kejelasan atas kondisi sosial-politik yang terjadi. Jika di saat seperti ini pemerintah malah membuka peluang pengampunan pajak, pesan yang diterima masyarakat bisa berbahaya, membuka keran ketidakpatuhan. Dampak jangka panjangnya, dikhawatirkan kepatuhan pajak bisa terkikis dan penerimaan negara justru rentan terganggu.
Kalau begitu, apa kebijakan alternatifnya? Pemerintah tentu tetap perlu memperluas basis pajak, karena rasio pajak Indonesia masih rendah dibanding negara lain di kawasan asia tenggara. Rasio pajak kita masih berkisar di 10–11% terhadap PDB, sementara negara tetangga seperti Thailand sudah di atas 14%, bahkan negara-negara yang tergabung dalam OECD memiliki rata-rata rasio pajak di atas 20%.
Pemerintah dapat melirik alternatif kebijakan untuk meningkatkan rasio pajak dan lebih sehat ketimbang amnesti berulang, yaitu ekstensifikasi pajak melalui underground economy. Transaksi di sektor ekonomi bawah tanah, mulai dari perdagangan daring informal, jasa tanpa izin, hingga aktivitas tunai yang tidak tercatat, perlu diteliti kembali. Jika sebagian transaksi tersebut bisa ditarik ke sistem resmi, maka basis pajak kita akan bertambah signifikan.
Setelah basis pajak bertambah, langkah berikutnya adalah memastikan pajak yang sudah ada benar-benar dipungut optimal. Langkah optimalisasi bisa dilakukan dengan pengawasan yang cerdas berbasis teknologi, pemanfaatan data big data transaksi, dan tentu saja penegakan hukum yang konsisten. Namun, kunci keberhasilan intensifikasi bukan sekadar represif, melainkan juga membangun kepercayaan.
Pada akhirnya, pajak bukan hanya soal angka, tapi juga soal rasa percaya. Wajib Pajak mau membayar jika yakin uang mereka dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika publik merasa pajak hanya habis untuk korupsi atau pemborosan pejabat, semangat kepatuhan akan luntur.
Inilah PR besar pemerintah dalam menaikan rasio pajak. Transparansi anggaran, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas belanja negara harus menjadi wajah utama kebijakan fiskal. Dengan begitu, Wajib Pajak tidak lagi merasa uang mereka terbuang percuma. Kepercayaan publik ini jauh lebih berharga daripada sekadar tambahan basis pajak jangka pendek lewat amnesti. Karena tanpa kepercayaan, sebesar apa pun basis pajak, penerimaan tidak akan optimal.