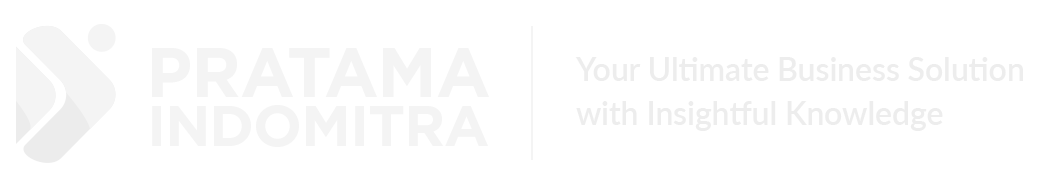Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda sementara penunjukan e-commerce sebagai pemungut PPh Pasal 22 memantik perdebatan yang wajar. Di satu sisi langkah itu dimaksudkan sebagai ruang napas bagi daya beli masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan tentang keadilan perlakuan antara pedagang online dan pedagang tradisional. Penundaan kebijakan bersifat temporer dan terkait waktu pelaksanaan penunjukan pemungut, bukan pembebasan tarif atau penghapusan kewajiban pajak bagi pelapak online. Keputusan penundaan itu diumumkan untuk memberi waktu melihat dampak stimulus ekonomi dan kesiapan pemangku kepentingan.
Sebelumnya, pemerintah melalui aturan teknis memang telah menetapkan skema di mana marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang memenuhi kriteria. Aturan ini dituangkan dalam PMK No 37 Tahun 2025 menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) seperti Shopee dan Tokopedia menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 (PPh Pasal 22) bagi pedagang yang melakukan transaksi di lokapasar. Skema semacam ini bukanlah ide baru, pemerintah menegaskan bahwa ini dimaksudkan untuk memperkuat basis pajak sektor digital sekaligus menyederhanakan kepatuhan bagi pelapak yang berjualan lewat platform.
Inti miskonsepsi publik adalah mengira bahwa pedagang di marketplace “dibebaskan” dari PPh final. Faktanya, pedagang online tetap dikenai PPh final UMKM sesuai ketentuan hanya mekanisme pemungutannya yang berbeda. Marketplace memungut dan menyetorkan dengan ambang omzet tertentu dan tarif final tertentu pada peredaran bruto, sementara pedagang tradisional umumnya harus melakukan penyetoran sendiri dan pelaporan rutin. Perbedaan mekanisme inilah yang membentuk sebuah convenience gap, kepatuhan menjadi lebih mudah bagi mereka yang bertransaksi melalui platform, sementara pedagang offline menghadapi beban administratif yang mendorong underreporting.
Kesenjangan kemudahan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi memengaruhi persaingan. Seorang pedagang pasar tradisional yang harus menyetorkan sendiri pajaknya menanggung waktu, risiko salah hitung, dan potensi denda pedagang online cukup “ditagih” lewat platform sebelum uang sampai ke tangan mereka. Akibatnya, pelaku offline bisa kalah bersaing bukan karena tarif pajak berbeda, melainkan karena akses terhadap kemudahan administrasi yang timpang. Jika pemerintah serius ingin menjaga keadilan dan sekaligus memperbaiki kepatuhan, fokusnya harus bergeser dari debat simplistik tunda atau jalankan ke perumusan mekanisme pemungutan yang setara.
Peran Pihak Ketiga Sebagai Pemenuhi Convenience Gap
Salah satu instrumen kunci untuk menutup celah ini adalah sistem pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2016), sistem pemotongan pajak mengizinkan pihak ketiga memotong atau memungut pajak yang terutang, sehingga pajak dipungut langsung saat penghasilan dibayarkan. Pendekatan ini terbukti memperoleh penerimaan lebih cepat, dengan biaya administrasi relatif rendah, dan efektif untuk memungut pajak penghasilan. Nurmantu menambahkan bahwa mekanisme pemotongan memudahkan dan menghemat biaya administrasi; bagi wajib pajak pemotong, kewajiban dapat dianggap terpenuhi sehingga mereka “nyaman”. Rosdiana (2014) bahkan menyoroti bahwa sistem pemotongan dapat menjadi opsi ampuh untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, third-party withholding bukan sekadar soal efisiensi, melainkan soal integritas basis pajak.
Melihat konteks e-commerce dan pasar tradisional, logikanya jelas: jika marketplace sebagai pihak ketiga dapat memungut PPh secara otomatis, mengapa pengelola pasar tidak diberi peran serupa? Menunjuk Pengelola Pasar, asosiasi pasar, atau koperasi sebagai agen pemungut disertai subsidi untuk perangkat kas dan integrasi sistem pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak akan membawa convenience yang sama ke kanal offline. Model ini bukan eksperimen teori semata, ia mereplikasi prinsip pemungutan efisien yang selama ini dipakai pada pemotongan gaji, bunga, dan transaksi finansial.
Akhirnya, wacana penundaan teknis seharusnya tidak mengaburkan tujuan yang lebih besar menciptakan kepatuhan yang adil dan berkelanjutan. Keadilan fiskal bukan hanya soal tarif yang sama, melainkan soal akses terhadap mekanisme yang memudahkan pemenuhan kewajiban. Dengan memperluas peran pihak ketiga dalam pemungutan dengan proteksi, pelatihan, dan digitalisasi untuk kanal offline pemerintah dapat menjembatani convenience gap, menutup celah penghindaran, dan menjaga level playing field tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
Menunda pelaksanaan teknis kadang diperlukan untuk menghindari dampak negatif pada konsumsi saat ekonomi tertekan merupakan argumen yang sah. Namun menunda tanpa menyelesaikan masalah administrasi hanya menangguhkan ketidakadilan. Kebijakan fiskal yang adil bukan hanya soal tarif yang sama, melainkan soal akses terhadap kemudahan untuk memenuhi kewajiban. Jika pemerintah ingin benar-benar menciptakan level playing field, ia harus menjembatani convenience gap dengan memindahkan beban administrasi dari pundak pelapak tradisional ke mekanisme yang memudahkan kepatuhan, sehingga kepatuhan meningkat, persaingan menjadi lebih adil, dan tujuan fiskal bisa tercapai tanpa melukai daya beli masyarakat.